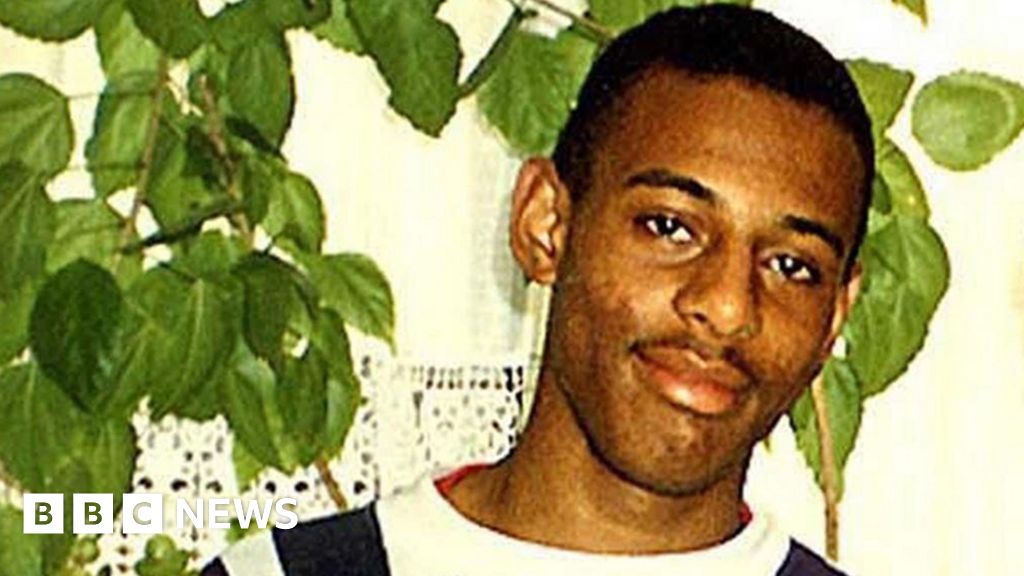REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fatwa pajak berkeadilan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memantik perdebatan baru tentang arah kebijakan fiskal di tengah tekanan daya beli dan wacana kenaikan tarif. Namun, polemiknya tidak berhenti pada soal tarif atau setuju-tidak setuju. Gagasan membatasi pajak hanya pada harta produktif dinilai membutuhkan langkah tegas pemerintah dan penegasan dalam aturan perpajakan.
Direktur Eksekutif Pratama–Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai sejak awal terdapat perbedaan asas antara cara pandang fatwa dan fondasi yang hidup dalam undang-undang pajak. Ia menyebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia tidak dibangun atas asas kemampuan finansial, melainkan bertumpu pada perolehan hak dan/atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Karena itu, selama wajib pajak masih memperoleh hak atau manfaat atas objek bumi dan bangunan, PBB tetap terutang setiap tahun sesuai UU PBB dan UU HKPD. Prianto menegaskan perubahan asas pemungutan PBB tidak bisa berjalan lewat wacana semata.
“Jadi, jika ada usulan agar PBB menggunakan asas ability to pay principle atau kemampuan secara finansial seperti usulan dari MUI, usulan tersebut harus tertuang di naskah akademik dulu," ujarnya kepada Republika, Rabu (26/11/2025).
Tanpa jalur itu, ia menilai gagasan belum dapat bekerja sebagai norma hukum dan masih terlalu dini untuk menakar dampaknya. Di titik ini, problem harta produktif menjadi semakin terbuka. Bahkan bila pintu legislasi kelak dimulai, pertanyaan operasionalnya tetap besar yakni apa ukuran produktif, siapa yang menetapkan, dan data apa yang dipakai.
Dalam praktik perpajakan, batas produktif–nonproduktif tidak selalu terang. Rumah tinggal pertama, tanah warisan yang belum digarap, ruko menganggur, hingga aset sosial-keagamaan dapat berpindah kategori tergantung definisi negara. Jika ukuran dan pendataan tidak rapi, pembatasan pajak pada harta produktif berisiko menjadi sumber sengketa baru di lapangan.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, menilai sebagian masukan MUI dapat direspons melalui kebijakan yang lebih cepat pada sektor dengan objek yang jelas. Ia mencontohkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor tertentu dapat ditangguhkan pengenaannya.
“Berdasarkan pengalaman empirik PPN untuk beberapa sektor tertentu bisa ditangguhkan pengenaannya. Misalnya, pemerintah buat kebijakan seperti masukan MUI dengan menangguhkan PPN untuk barang kebutuhan pokok itu,” kata Lukman kepada Republika.
Lukman juga mengingatkan pemerintah agar menyeimbangkan langkah pajak dan tidak hanya bertumpu pada intensifikasi. “Ini kan tergantung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kalau intensifikasi berarti pemerintah harus meningkatkan tarif pajak. Kalau ekstensifikasi pemerintah harus memperluas wajib pajak dan objek pajak. Saat ini pemerintah lebih memilih cara yang mudah yakni intensifikasi misalkan menaikkan PPN dari 10 persen ke 11 persen, sampai 12 persen. Cukai rokok dinaikkan sampai lebih 50 persen. Tetapi sangat kurang melakukan ekstensifikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak sebenarnya telah tersedia. “Ini sebenarnya sudah mulai jalan, kalau kita punya bukti pembayaran zakat maka bisa dipakai untuk mengurangkan pajak kita,” kata dia.
Sementara itu, Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan pemerintah pada prinsipnya sudah memakai asas daya pikul dalam aturan yang berlaku. Ia menekankan keberadaan penghasilan tidak kena pajak, ambang batas PPN, serta perlakuan khusus bagi UMKM. Terkait PBB-P2, Bimo menegaskan kewenangan pemajakannya berada pada pemerintah daerah, termasuk keringanan bagi aset sosial-keagamaan yang bersifat nirlaba. Ia juga menyebut bahan pokok tidak dikenakan PPN sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
.png)
 23 minutes ago
1
23 minutes ago
1