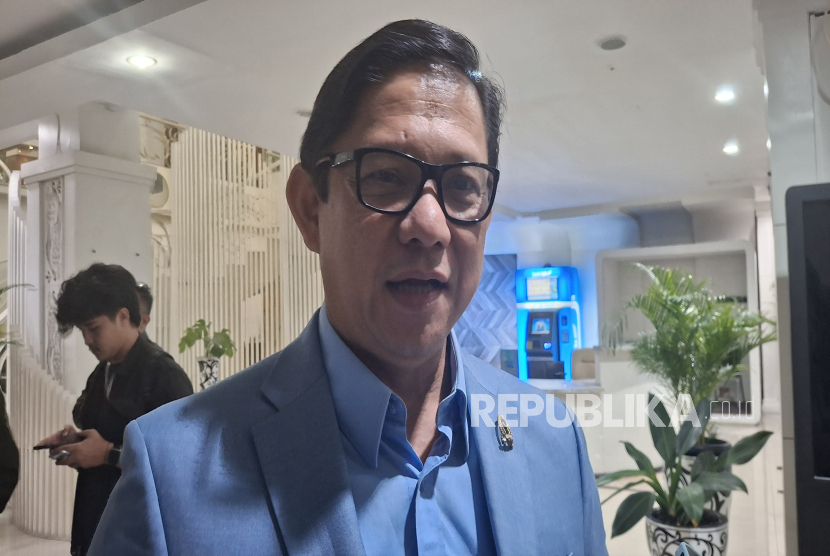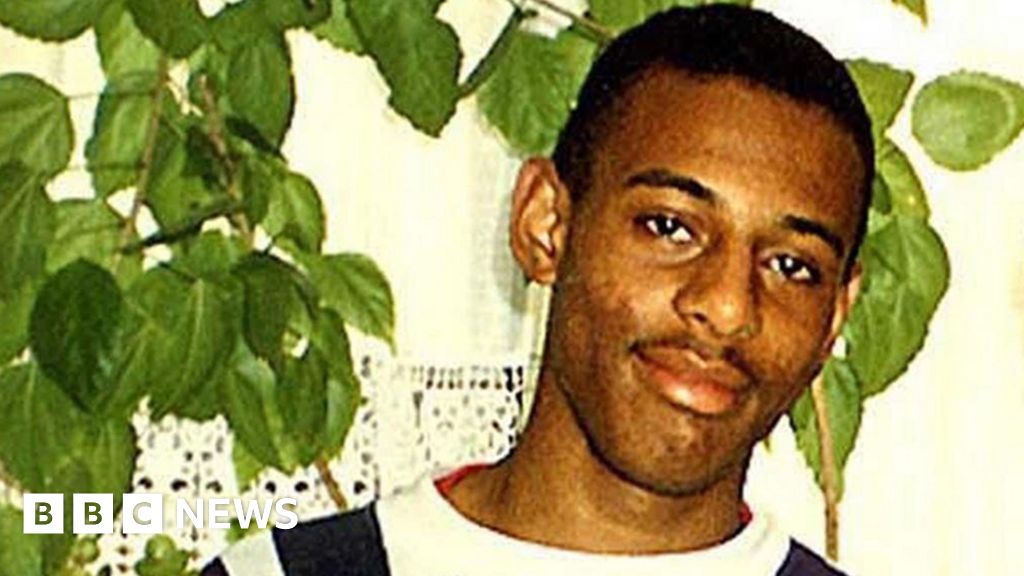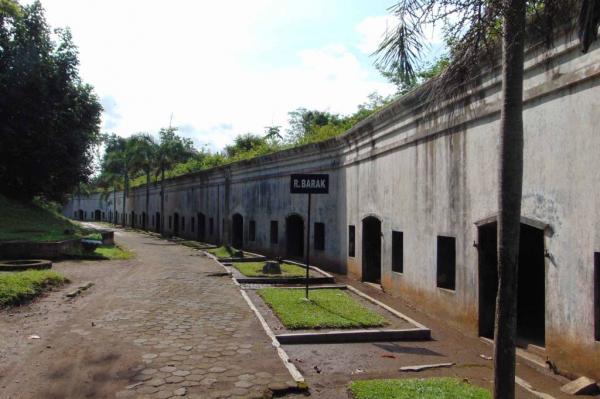REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Mohamad Dian Revindo menilai praktik thrifting tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan perdagangan barang bekas, melainkan harus dilihat dari akar persoalan tata kelola impor. Ia menegaskan tren thrifting memiliki sejarah panjang dan tetap eksis meski menghadapi larangan resmi.
“Thrifting pada awalnya adalah suatu upaya konsumen untuk berhemat, mendapat barang berkualitas dengan harga murah. Meskipun kemudian industrialisasi dan produksi massal membuat produk pakaian baru menjadi sangat murah, kegiatan thrifting tidak pernah benar-benar hilang,” kata Revindo kepada Republika, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir muncul motivasi tambahan di kalangan pengguna, yakni kesadaran untuk meminimalkan dampak lingkungan dari industri fesyen. Hal ini, lanjut Revindo, menjadi alasan mengapa meski dilarang, thrifting tetap populer di Indonesia. Harga terjangkau, kualitas produk, hingga pilihan barang bermerek dan unik membuat konsumen sulit beralih ke produk baru.
“Selain itu, thrifting dianggap sebagai bentuk konsumsi yang lebih berkelanjutan, karena dapat mengurangi limbah tekstil dan mendukung daur ulang,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai thrifting tidak bisa dipandang sebagai substitusi sempurna bagi produk domestik. “Ada segmen konsumen yang memang mengincar produk thrifting karena brand atau style, yang belum tentu akan beralih ke produk lain,” kata Revindo.
Revindo menekankan fokus kebijakan tidak seharusnya langsung diarahkan pada pelaku usaha thrifting, melainkan pada penegakan tata kelola impor. “Semua upaya pemerintah untuk menertibkan impor harus didukung. Impor yang mengancam industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) Indonesia dapat berasal dari impor ilegal maupun impor yang legal tetapi tidak fair, baik produk baru maupun bekas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, impor ilegal menimbulkan dampak ganda bagi perekonomian. Negara kehilangan pemasukan bea masuk, sementara industri tekstil dan pakaian jadi nasional terpukul oleh serbuan barang murah. Selain itu, ada pula impor legal tetapi tidak fair, termasuk praktik dumping.
Revindo menilai Indonesia perlu memperkuat instrumen trade defence. “Perlu penguatan trade defence/trade remedy (instrumen antidumping, antisubsidi, dan safeguard measure) untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan internasional negara lain yang tidak sehat.”
Pemerintah telah melarang impor pakaian bekas melalui Permendag Nomor 18 Tahun 2021. Larangan ini muncul karena kekhawatiran dampak ekonomi dan kesehatan. “Hal ini didasari oleh kekhawatiran thrifting dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri, yang dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja dan memicu masalah kesehatan akibat pakaian bekas yang mungkin mengandung bakteri,” ujarnya.
Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pengawasan di lapangan. “Tinggal bagaimana mengamankan impor ilegal ini, baik yang masuk lewat jalur pelabuhan kecil ataupun transaksi daring,” katanya.
Menurut Revindo, selain penegakan impor, pemerintah juga perlu memberi ruang bagi perkembangan pasar barang bekas dalam negeri sehingga pelaku usaha tidak mati karena regulasi. “Yang perlu dihidupkan adalah bursa atau pasar pakaian bekas berkualitas,” ujarnya.
Ia menyarankan agar brand lokal mulai menggalang program pengumpulan pakaian bekas layak pakai dan diberikan insentif bila perlu. Kampanye masyarakat untuk menjual barang bekas perlu digerakkan guna mengurangi budaya menumpuk barang.
“Dengan cara ini maka industri TPT dalam negeri akan terlindungi dari impor ilegal dan dumping, tetapi bursa thrifting dalam negeri juga tetap semarak dan memberi kesempatan kerja bagi UKM yang memperdagangkannya,” kata Revindo.
.png)
 1 hour ago
1
1 hour ago
1