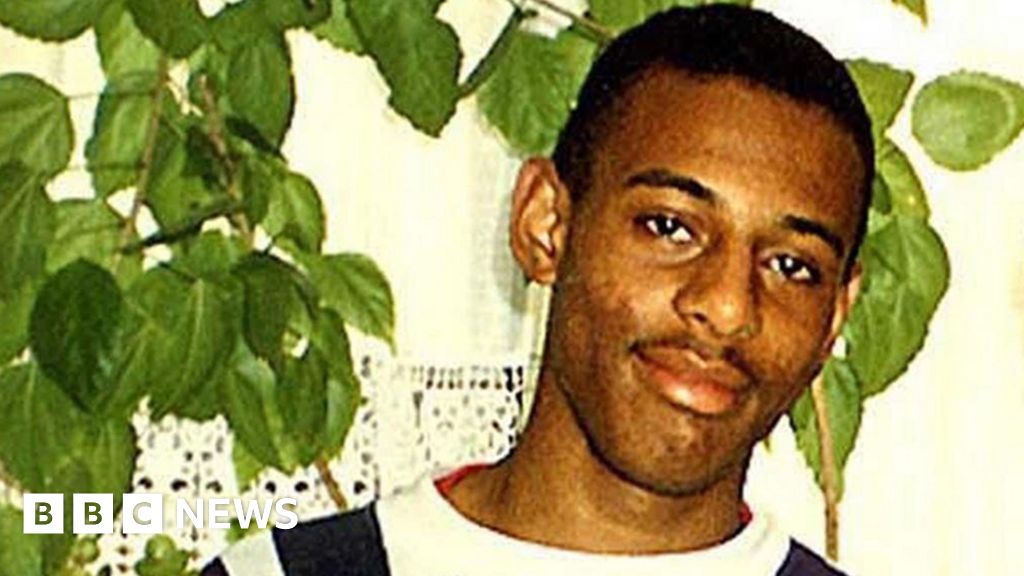Oleh: Febrin Anas Ismail, Guru Besar dan Anggota Pusat Studi Bencana Universitas Andalas
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- “Kalau sudah separah ini, apa lagi yang kita tunggu?” Pertanyaan seperti itu berulang kali terdengar dari warga yang berusaha bertahan di tengah banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025.
Dengan 867 korban meninggal, ratusan orang hilang, ribuan terluka, dan hampir satu juta jiwa mengungsi, bencana ini jelas melampaui batas fenomena alam biasa. Yang terpampang di hadapan publik adalah sebuah krisis kemanusiaan yang menelanjangi kerentanan struktural di tiga provinsi sekaligus.
Kerusakan fisik yang tercatat menambah bobot persoalan. Lebih dari 121 ribu rumah rusak, ratusan jembatan runtuh, ratusan sekolah dan fasilitas kesehatan lumpuh, serta banyak ruas jalan nasional terputus berhari-hari. Jaringan listrik dan komunikasi padam, sementara pergerakan logistik di seluruh Sumatera tersendat. Pada kondisi semacam ini, batas administratif provinsi seolah kehilangan relevansinya; kerusakan yang saling berkait menunjukkan bahwa ini adalah ancaman terhadap keberlangsungan hidup jutaan warga, bukan lagi sekadar urusan satu atau dua pemerintah daerah.
Pengalaman dari kejadian-kejadian sebelumnya memberi pelajaran penting tentang keterbatasan kapasitas daerah. Jembatan Manunggal, akses vital menuju Batusangkar, yang rusak akibat galodo Merapi pada Mei 2024 hingga hari ini belum kembali berfungsi karena minimnya anggaran dan tenaga teknis. Jika satu jembatan saja memakan waktu hampir dua tahun tanpa kepastian, bayangkan skala kesulitan memulihkan ratusan jembatan yang rusak dalam banjir kali ini. Gambaran tersebut menunjukkan betapa timpangnya beban yang harus dipikul oleh daerah tanpa didukung perangkat fiskal yang memadai.
APBD, betapapun besar pada sebagian provinsi, tidak pernah disiapkan untuk memulihkan ratusan ribu pengungsi, memperbaiki jaringan logistik, membangun ulang infrastruktur vital, dan menata kembali kehidupan sosial secara bersamaan. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan status “bencana daerah” bukan hanya kurang tepat, tetapi juga berpotensi memperpanjang ketidakpastian yang dialami para penyintas. Respons yang terfragmentasi hampir pasti menghasilkan pemulihan yang timpang dan tertunda.
Memang, pemerintah pusat memiliki prosedur yang harus ditaati sebelum menetapkan status Bencana Nasional. Kekhawatiran terkait akurasi data, potensi penyalahgunaan anggaran, atau kelengkapan prasyarat hukum sering kali menjadi alasan penundaan. Namun kehati-hatian prosedural tidak boleh memadamkan urgensi kemanusiaan. Sejarah penanganan bencana di Indonesia menunjukkan bahwa jeda waktu, betapapun kecil, sering berubah menjadi rentang kerentanan baru: bantuan tak kunjung tiba, layanan publik macet, dan ketegangan sosial meningkat.
Banjir Sumatera menunjukkan perlunya satu komando yang kuat dan lintas-wilayah. Pemulihan jalan nasional, distribusi logistik antarprovinsi, dan perbaikan fasilitas umum bukanlah tugas yang bisa didistribusikan secara terpisah ke masing-masing daerah. Penetapan Bencana Nasional bukan sekadar label administratif; ia membuka akses penuh pada sumber daya negara, termasuk peluang masuknya bantuan internasional yang hanya bisa disalurkan melalui mekanisme nasional.
Dari sudut pandang keadilan, status nasional merupakan bentuk pengakuan negara bahwa keselamatan warga tidak boleh ditentukan oleh besaran APBD. Warga Aceh, Sumut, dan Sumbar menghadapi ancaman yang sama dan berhak menerima perlindungan yang setara. Prinsip sederhana ini mudah diabaikan dalam tarik-menarik kebijakan, padahal justru menjadi dasar bagi hadirnya negara dalam situasi genting.
Menimbang skala kerusakan dan kompleksitas dampak yang mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, dan layanan publik, sulit mencari argumen yang meyakinkan bahwa mekanisme daerah masih memadai. Dalam kondisi seperti ini, negara perlu melangkah lebih jauh, bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai penanggung jawab utama pemulihan dan keselamatan warganya.
Karena itu, Banjir Sumatera 2025 layak ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Namun keputusan tersebut harus dibarengi komitmen transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat agar seluruh proses penanganan benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling terpukul. Status tanpa tindakan hanyalah tanda kosong; yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk menerjemahkannya menjadi langkah nyata di lapangan.
Pada akhirnya, setiap keputusan akan diuji oleh dampaknya pada manusia. Banjir Sumatera mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak boleh terjebak dalam belitan prosedur semata, melainkan harus kembali pada tujuan yang paling mendasar: melindungi kehidupan.
.png)
 2 hours ago
2
2 hours ago
2