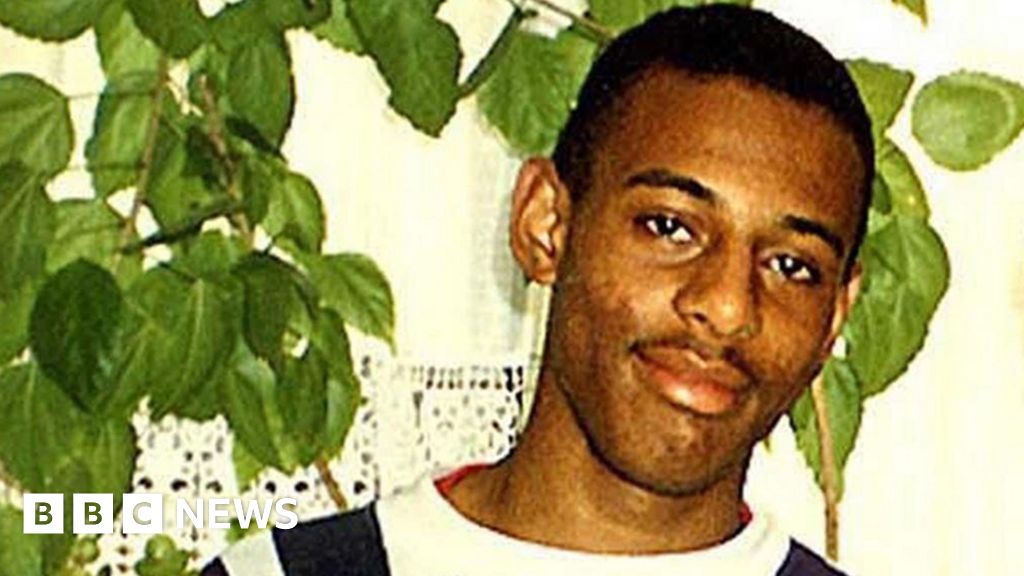Ari J. Palawi
Ari J. Palawi
Kebijakan | 2025-11-12 23:25:08
 Contoh baik Pemda Aceh Tengah. (Foto koleksi pribadi).
Contoh baik Pemda Aceh Tengah. (Foto koleksi pribadi).
Di negeri ini, hampir tak ada ruang yang bebas dari wajah kekuasaan. Setiap baliho, spanduk, layar televisi, bahkan laman resmi lembaga publik menampilkan potret pejabat: tangan melambai, senyum mengembang, dan tagline yang meniru bahasa moral. Dari jalan-jalan provinsi hingga universitas, negara tampil melalui citra, bukan kerja.
Fenomena ini tampak ringan, tapi sebenarnya berbahaya: kita sedang hidup di dalam republik wajah, di mana representasi menggantikan kinerja, dan pencitraan menenggelamkan akal sehat.
Sebagai pendidik di universitas negeri selama lebih dari dua dekade, saya sering menyaksikan bagaimana ruang publik akademik maupun birokratik kehilangan keberanian untuk jujur. Saat menjabat ketua jurusan, saya memilih tidak menempelkan foto diri di setiap kegiatan. Itu bukan kebajikan—hanya keengganan untuk ikut dalam parade simbol yang semakin absurd. Karena jabatan, pada akhirnya, hanyalah amanah yang singkat—bukan altar untuk memuja diri.
Namun, apa yang dulu terasa janggal kini menjadi lumrah. Foto pejabat harus muncul di setiap proyek, setiap pelatihan, setiap laporan. Bahkan di lembaga yang seharusnya mengajarkan etika rasional, citra pribadi kini menggantikan makna publik.
Dari Orde Simbol ke Demokrasi Pencitraan
Tradisi ini bukan kebetulan. Ia berakar dalam sejarah panjang politik simbolik Indonesia. Pada masa Orde Baru, wajah pemimpin menjadi lambang negara—dipasang di sekolah, kantor, dan ruang rapat untuk menanamkan loyalitas. Setelah reformasi, wajah tunggal itu memang menghilang, tetapi logika simboliknya tetap hidup: kini setiap pejabat merasa berhak memiliki ruang visual sendiri.
Dalam konteks komunikasi politik modern, fenomena ini dikenal sebagai personal branding governance—transformasi fungsi publik menjadi pertunjukan individu. Pejabat lokal dan nasional di Indonesia berlomba membeli ruang di media untuk menjaga eksposur personal mereka, menciptakan “demokrasi pencitraan” yang tampak ramai tapi miskin makna.
Kita pun menyaksikan paradoks baru: semakin banyak wajah yang tersenyum, semakin sulit menemukan kerja yang nyata.
Ketika Publikasi Mengalahkan Pelayanan
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), praktik belanja publik untuk kegiatan seremonial dan publikasi kerap melampaui proporsinya, terutama di sektor pemerintahan daerah. Data dari berbagai sumber mencatat pola pemborosan anggaran publikasi dan perjalanan dinas yang tidak berbanding lurus dengan kinerja layanan publik. Selain itu, juga ditemukan belanja promosi dan publikasi yang tidak efisien, termasuk penggunaan dana untuk kegiatan pencitraan pejabat tanpa justifikasi manfaat langsung bagi masyarakat.
Fakta-fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa ruang komunikasi publik di Indonesia telah bergeser dari fungsi pelayanan menuju arena promosi personal. Pesan kebijakan berubah menjadi katalog wajah dan slogan.
Padahal, hakikat komunikasi publik adalah melayani, bukan menampilkan diri. Pejabat publik seharusnya mengembalikan pusat orientasi pelayanan kepada warga negara, bukan pada citra pribadi. Namun di Indonesia, publikasi sering kali justru memindahkan pusat itu ke wajah pejabat—bukan pada masyarakat yang membiayai gajinya.
Yang paling berbahaya dari semua ini bukanlah gambar di baliho, melainkan kebiasaan berpikir yang ia bentuk: bahwa pejabat adalah pusat semesta, sementara publik hanyalah penonton yang harus kagum.
Ketika Media Kehilangan Jarak Kritis
Banyak media kini menjadi bagian dari mesin simbol itu. Hubungan patronase antara pejabat dan redaksi menciptakan lanskap komunikasi yang timpang. Berita kehilangan daya kritis, berganti menjadi dokumentasi seremonial: siapa meresmikan apa, di mana, dan dengan siapa berfoto.
Dalam situasi ini, fungsi kontrol media mati perlahan. Kritik digantikan unggahan. Transparansi berubah menjadi dekorasi. Demokrasi kehilangan oksigennya.
Kita hidup dalam dunia yang sibuk menampilkan “kesuksesan,” tetapi enggan mempertanyakan proses. Wajah pejabat muncul setiap hari, tapi angka kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi moral tetap berjalan tanpa malu.
Kedaulatan yang Disandera Simbol
Konstitusi Republik Indonesia menegaskan dengan jelas: “Kedaulatan berada di tangan rakyat” (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945). Namun dalam praktiknya, rakyat sering hanya menjadi penonton di panggung kekuasaan. Simbol yang seharusnya merepresentasikan pelayanan berubah menjadi alat penguasaan. Pejabat yang seharusnya pelayan publik kini lebih sibuk mempertahankan mitos wibawa ketimbang akuntabilitas.
Padahal dalam etika tata kelola global disebutkan bahwa pejabat publik wajib menghindari setiap bentuk konflik kepentingan—baik material maupun simbolik. Pencitraan berlebihan dapat dibaca sebagai penyalahgunaan simbol negara untuk kepentingan pribadi.
Langkah kecil seperti kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung (2023) yang melarang penggunaan foto pejabat di baliho dan media luar ruang sebenarnya menawarkan preseden baik. Surat Edaran Gubernur No. 045.2/05/2023 secara tegas menyebut bahwa “setiap publikasi pemerintah harus mengutamakan pesan kebijakan, bukan wajah pejabat.” Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 000.9.3.3/6674/SJ (2023), yang mendorong penertiban penggunaan gambar pejabat pada reklame resmi.
Sayangnya, di banyak daerah, kebijakan serupa tidak diindahkan. Bahkan beberapa media publik justru berlomba menayangkan potret seremonial pejabat sebagai “berita utama.” Akibatnya, wajah menjadi instrumen kekuasaan baru—lebih efektif dari peraturan, lebih populer dari kinerja.
Demokrasi yang Terlalu Personal
Gejala paling serius dari semua ini adalah matinya rasionalitas publik. Demokrasi yang seharusnya berbasis pada ide dan kinerja kini berubah menjadi kontes personal. Loyalitas emosional lebih berpengaruh daripada rekam jejak kebijakan. Kita melihat logika yang sama merembes ke birokrasi dan akademik: yang menonjol bukan gagasan, tapi kedekatan; bukan kerja, tapi simbol.
Akibatnya, integritas menjadi beban. Pejabat yang tenang dan sopan lebih disukai daripada yang berpikir kritis. Dan bangsa yang terus-menerus memuja wajah akan kesulitan melahirkan pemimpin yang berani menatap realitas.
Menurunkan Wajah, Mengangkat Akal Sehat
Kita perlu memulihkan logika sederhana dalam tata kelola publik: bahwa jabatan bukan milik pribadi, dan pelayanan bukan alat pencitraan. Pejabat tidak perlu dipajang; cukup bekerja dengan benar. Media tidak perlu menyanjung; cukup melaporkan dengan jujur. Dan masyarakat tidak perlu memuja; cukup mengawasi dengan cerdas.
Kehormatan jabatan bukan diukur dari seberapa sering wajahnya tampil di layar, tetapi dari seberapa dalam ia bekerja bagi sesama manusia. Kedaulatan rakyat hanya bisa ditegakkan jika nalar publik kembali hidup. Dan nalar publik hanya akan hidup jika kita berani menghentikan satu kebiasaan sederhana: mengganti kerja dengan citra, dan kebenaran dengan wajah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
.png)
 3 hours ago
2
3 hours ago
2