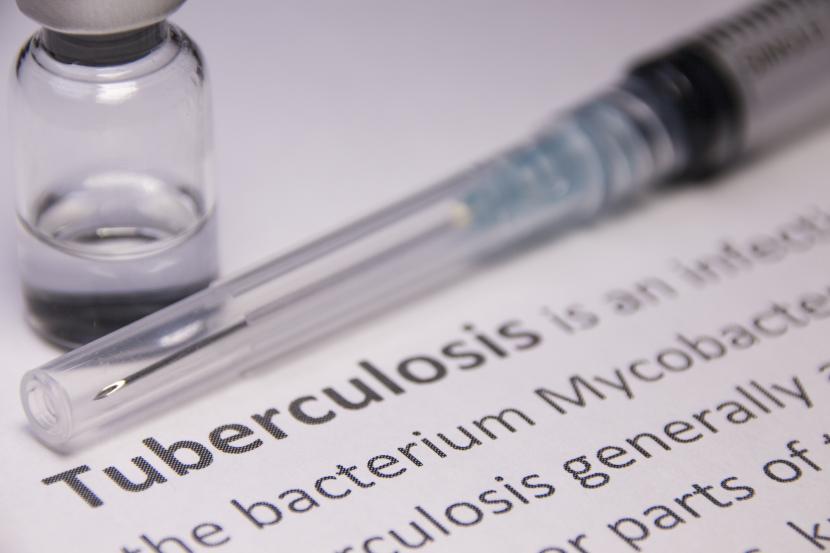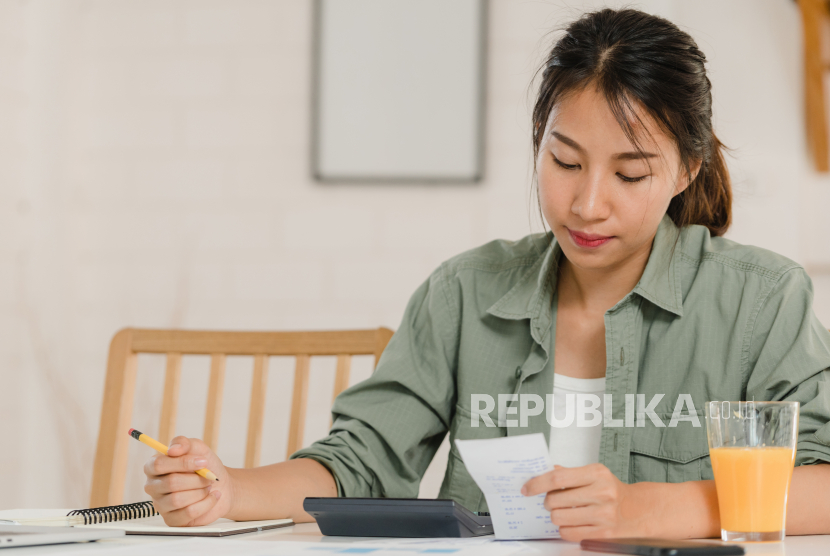REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan luas laut Indonesia mencapai lebih dari 70 persen dari total seluruh wilayah Indonesia. Posisi Indonesia juga sangat strategis karena terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua serta dua samudra.
"Hal ini menjadikan Indonesia memiliki keragaman hayati yang tinggi, baik di darat maupun di laut," ujar Susan saat dihubungi Republika di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Susan menyampaikan jumlah nelayan pada 2023 tercatat sebanyak 2.773.538 jiwa. Akan tetapi hingga saat ini, data jumlah nelayan tersebut belum memisahkan antara nelayan industri dengan nelayan skala kecil dan/atau tradisional.
Berdasarkan UU No 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa kategori nelayan kecil adalah mereka yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT. Namun, lanjut Susan, kategori skala GT ukuran kapal nelayan kecil tersebut telah dihapus dalam UU Cipta Kerja.
"Jika merujuk kepada UU 7/2016 yang mengategorikan nelayan kecil sebagai nelayan di bawah 10 GT, maka pada 2023 jumlah kapal nelayan kecil di Indonesia yaitu sebanyak 775.449 unit kapal (sekitar 92,7 persen)," ucap Susan.
Angka tersebut terdiri atas perahu tanpa motor, perahu motor, dan perahu berukuran
Dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri atas 70 persen laut dan populasi nelayan kecil yang mendominasi sektor perikanan tangkap laut, Susan menyebut peran nelayan kecil sangat strategis. Mereka memasok sumber daya perikanan laut yang dimulai dari desa-desa pesisir. Dalam konteks ini, lanjut Susan, kondisi laut yang sehat dan dapat diakses (tidak diprivatisasi) berperan penting sebagai sumber pangan strategis yang menghidupi nelayan kecil sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya protein hewani yang dibutuhkan bangsa.
"Nelayan kecil sangat bergantung kepada laut yang sehat dan bisa diakses untuk memastikan ketahanan pangan dari sektor perikanan tangkap laut yang pada ujungnya dapat menciptakan kedaulatan pangan perikanan laut," ujar Susan.
Susan menyebut tantangan terbesar yang dihadapi nelayan kecil dan tradisional dalam menjaga ketersediaan pangan laut terbagi dalam tiga konteks utama yang saling berhubungan. Pertama, kondisi kesehatan ekosistem laut (terumbu karang, mangrove, dan lamun) serta perubahan iklim. Kedua, ekspansi industri eksploitatif dan ekstraktif seperti industri perikanan skala besar dan pertambangan. Ketiga, ekspansi industri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti industri pariwisata, konservasi, serta infrastruktur seperti reklamasi.
"Ekspansi industri eksploitatif dan ekstraktif serta industri jasa yang masif menyebabkan rusak dan/atau tercemarnya ekosistem laut," tutur Susan.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menyebabkan nelayan kecil dan tradisional semakin sulit mendapatkan ikan sehingga hasil tangkapan mereka menurun drastis. Hal ini ditemukan KIARA di kampung nelayan pesisir utara Manado (Sulawesi Utara), Pulau Kodingareng (Sulawesi Selatan), Pulau Wawonii (Sulawesi Tenggara), Pulau Bangka (Bangka Belitung), Teluk Weda (Maluku Utara), bahkan di Teluk Jakarta yang dekat dengan pusat pemerintahan.
"Kondisi ini diperparah dengan semakin masifnya Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana dari 77 PSN yang ditetapkan dalam Perpres 12/2025 tentang RPJMN, terdapat 33 PSN yang beririsan dengan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil," lanjut Susan.
Selain itu, Susan juga menyoroti berbagai peraturan perundang-undangan yang menciptakan tantangan terhadap ketersediaan pangan laut, yaitu kebijakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), UU Cipta Kerja, PP dan Permen KP tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, PP dan Permen KP tentang Penangkapan Ikan Terukur, dan berbagai peraturan lainnya.
Berbagai hal tersebut, baik pada level kebijakan maupun peraturan, ekspansi industri yang berpotensi bahkan telah terbukti merusak ekosistem pesisir dan laut, serta krisis iklim yang belum dimitigasi maupun diadaptasi pemerintah, menjadi tantangan terbesar yang dihadapi nelayan tradisional dalam menjaga ketersediaan pangan laut.
"Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya laut masih belum berpihak kepada nelayan kecil dan perlindungan ekologi pesisir dan laut, yang tentu saja berimplikasi terhadap ketahanan pangan perikanan," ujar Susan.
Menurut Susan, kebijakan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah kontradiktif dengan wacana keberpihakan terhadap nelayan, ekologi sebagai panglima, dan penciptaan ketahanan pangan. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah mewujudkan ketahanan pangan jika terdapat 33 PSN yang beririsan dengan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
"Selain itu, tidak adanya upaya serius dan konkret yang dilakukan pemerintah mengatasi krisis iklim yang tengah terjadi di Indonesia," lanjut Susan.
Susan mencontohkan ironi di wilayah pulau-pulau kecil seperti Pulau Masalembu, di mana melimpahnya hasil tangkapan nelayan berbanding terbalik dengan serapan hasil tangkapan tersebut. Ia menyebut tidak terdapat fasilitas seperti TPI dan SPBU/SPBN sehingga hasil tangkapan ikan nelayan kecil sering tidak terbeli dan akhirnya dibuang, menyebabkan kerugian besar bagi mereka.
"Harga Acuan Ikan sebagaimana tertera dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 29 Tahun 2024 juga tidak diimplementasikan di lapangan karena tidak adanya infrastruktur dan fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk menyerap hasil tangkapan ikan nelayan," ungkap Susan.
Untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut sekaligus menjamin akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan tradisional, terhadap pangan laut yang terjangkau dan bergizi, pemerintah seharusnya melakukan perlindungan melalui pengakuan profesi nelayan, termasuk perempuan yang secara de facto berprofesi sebagai nelayan.
Susan juga mendesak pemerintah memberikan perlindungan terhadap wilayah atau ruang tangkap nelayan tradisional sesuai kondisi geografis masing-masing wilayah, menghentikan dan mengevaluasi total industri jasa serta industri ekstraktif yang berpotensi merusak ekosistem pesisir dan laut. Ia meminta pemerintah mengakui bentuk-bentuk konservasi berbasis masyarakat yang dilakukan masyarakat adat dan komunitas lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Selain itu, ujar Susan, pemerintah harus menjalankan prinsip FPIC (Free Prior and Informed Consent) atau persetujuan di awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi bagi masyarakat pesisir, serta prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pembangunan. Dengan begitu, masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan tradisional, akan berdaulat dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK No. 3 Tahun 2010.
"Lindungi dan akui profesi nelayan. Lestarikan ekosistem laut, hentikan ekspansi industri, dan laut untuk nelayan!" tegas Susan.
.png)
 4 hours ago
4
4 hours ago
4