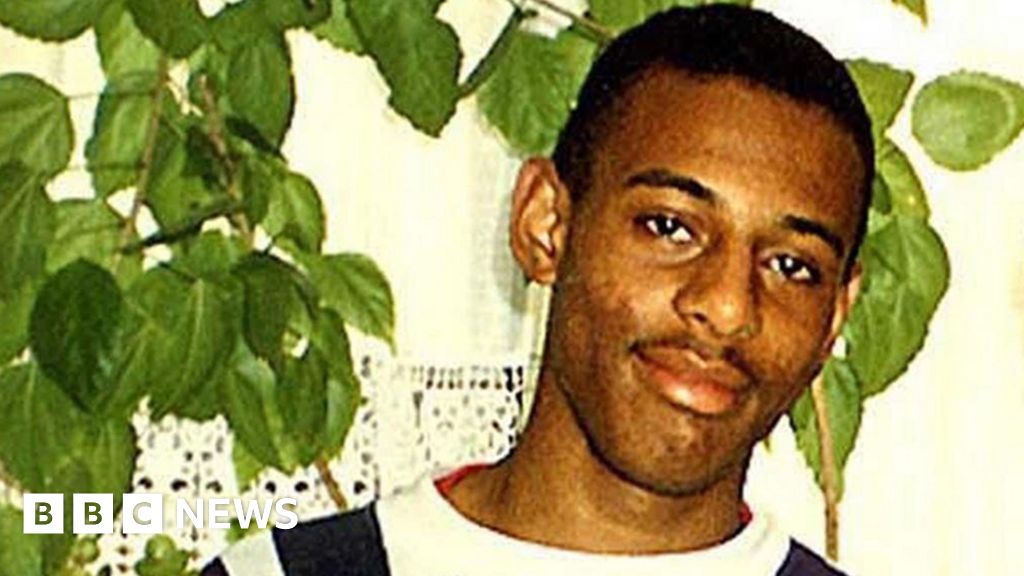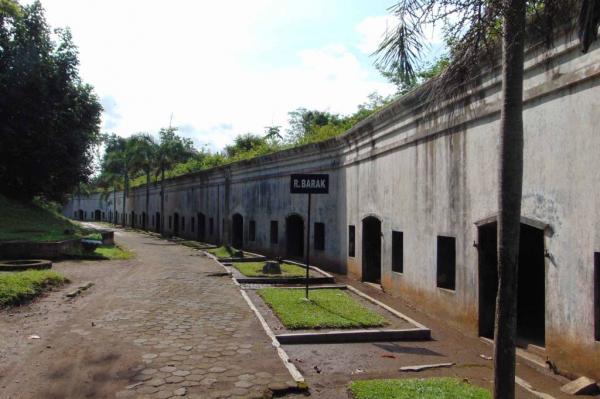REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak pemerintah agar memastikan perlindungan hak masyarakat adat dan lokal dalam implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC), dokumen iklim nasional yang baru dirilis menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brazil, November 2025. Celios menilai strategi mitigasi iklim dalam SNDC masih bias terhadap pendekatan berbasis lahan dan berpotensi menimbulkan konflik tenurial di wilayah adat.
Peneliti Celios, Viky Arthiando, menjelaskan bahwa salah satu poin dalam SNDC mencantumkan rencana rehabilitasi lahan terdegradasi melalui pengembangan energy plantation atau Hutan Tanaman Energi (HTE). Menurutnya, pendekatan ini berisiko menimbulkan konflik baru di wilayah dengan hak kelola masyarakat adat dan lokal yang belum diakui secara hukum.
“Pengembangan Hutan Tanaman Energi dalam skala besar berpotensi menimbulkan konflik tenurial baru dan mengancam ruang hidup masyarakat adat,” ujar Viky dalam pernyataan tertulis Celios, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).
Ia juga menyoroti strategi pemerintah yang mendorong pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) dengan target B40 pada 2025. Kebijakan ini, menurut Celios, dijalankan tanpa mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah ekspansi perkebunan sawit atau tanaman energi ke kawasan hutan dan lahan pangan. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, kebijakan tersebut berisiko memicu deforestasi dan memperparah ketimpangan agraria.
Celios menilai ketidakjelasan definisi “hutan” dalam dokumen SNDC dapat mengaburkan klaim penurunan deforestasi. Strategi mitigasi di sektor pertanian juga dinilai belum berpihak pada petani kecil, karena beban pengurangan emisi justru ditumpukan pada mereka, bukan pada korporasi besar atau proyek-proyek skala nasional seperti food estate yang justru berkontribusi pada pembukaan lahan besar-besaran.
Celios menyoroti proyek food estate di Merauke yang berpotensi mengonversi dua juta hektare kawasan hutan. Berdasarkan analisis lembaga tersebut, proyek itu dapat menghasilkan tambahan emisi karbon hingga 782,45 juta ton CO₂ atau setara kerugian karbon sekitar Rp47,7 triliun, sehingga meniadakan manfaat mitigasi di sektor lain.
Direktur Studi Sosio-Bioekonomi Celios, Fiorentina Refani, menilai strategi mitigasi di sektor energi juga belum konsisten dengan semangat coal phase-out. Dokumen SNDC justru menonjolkan penggunaan Clean Coal Technology (CCT) seperti supercritical dan ultra-supercritical sebagai solusi transisi, yang menurutnya hanya memperpanjang ketergantungan pada batubara.
“Pendekatan ini menunda dekarbonisasi yang sesungguhnya. Penggunaan teknologi seperti co-firing biomassa dan CCS/CCUS tidak menyelesaikan akar masalah, justru memperpanjang usia PLTU,” kata Fiorentina.
Ia juga menyoroti absennya pengakuan terhadap sektor industri hilirisasi nikel dan baja sebagai sumber emisi besar yang sulit dikurangi (hard to abate). Padahal, ekspansi industri tersebut bergantung pada PLTU captive di kawasan industri yang berkontribusi langsung terhadap kenaikan emisi nasional.
Celios merekomendasikan pemerintah segera menetapkan no-go zone atau larangan izin pertambangan dan pembangunan smelter di pulau-pulau kecil serta wilayah kelola masyarakat adat. Selain itu, Celios juga mendorong percepatan pembahasan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan hukum yang mendesak.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa keberhasilan implementasi SNDC tidak hanya bergantung pada aspek teknis mitigasi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pendanaan iklim yang berkelanjutan. Ia menilai kebutuhan investasi iklim sebesar 472,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.845 triliun sebagaimana tercantum dalam SNDC harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan kemandirian nasional.
“Kita memiliki banyak opsi pembiayaan domestik tanpa membebani kelompok rentan, seperti penerapan windfall profit tax dan pajak kekayaan. Pajak progresif terhadap kelompok superkaya dapat menjadi sumber pendanaan untuk mengendalikan kerusakan ekologis dan membiayai transisi iklim,” ujar Bhima.
Celios menegaskan bahwa tanpa perlindungan hak adat, keadilan sosial, dan reformasi kebijakan energi, transisi energi Indonesia berisiko menjadi proyek “hijau semu” yang menggantikan satu bentuk eksploitasi dengan bentuk lainnya.
.png)
 1 month ago
22
1 month ago
22