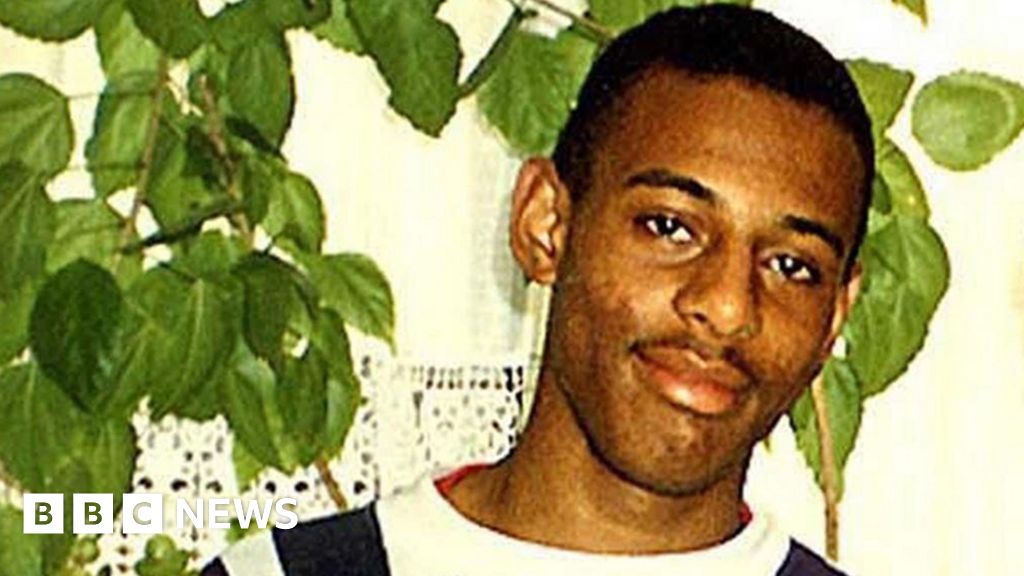Oleh : Jani Purnawanty, Dosen dan Peneliti di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Grantee Impact Sheed Funding (ISF) by Pulitzer Center 2022 & 2023 tema Climate Change
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat sungai membawa gelondongan kayu dan desa-desa luruh bersama lumpur, yang runtuh sebenarnya bukan hanya tanah di lereng Sumatera, melainkan fondasi pengawasan publik republik ini. Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar peristiwa hidrometeorologi, ini adalah peringatan keras bahwa taring ekologis Indonesia telah tumpul.
Pertanyaannya tidak lagi “mengapa pemerintah gagal?”, melainkan “ke mana perginya kekuatan penyeimbang yang seharusnya menjaga hutan dan sungai ketika negara abai?” Jika alam kini tergerus tanpa perlindungan, itu karena republik ini kehilangan taring ekologisnya.
Apa yang saat ini terjadi di Indonesia sejalan dengan apa yang disebut oleh ekonom politik George Stigler sebagai regulatory capture, kondisi ketika lembaga pengawas justru dikuasai oleh pihak yang seharusnya diawasi. Dalam konteks lingkungan, bentuknya lebih ekstrem: izin, kebijakan, dan tata ruang terseret masuk dalam orbit kepentingan ekonomi-ekstraktif. Namun, apa yang terjadi di Indonesia mengalami sesuatu yang lebih jauh dari sekadar regulatory capture. Ilmuwan lingkungan seperti Rob Nixon menyebut fase ini sebagai ecological capture, sebuah kondisi ketika bukan hanya lembaga negara yang “ditangkap”, tetapi juga aktor-aktor masyarakat sipil yang seharusnya menjadi pengawas: pers, kampus, LSM, komunitas adat, bahkan ruang publik itu sendiri.
Ketika check and balance ekologis luluh, bencana bukan hanya mungkin, bencana menjadi keniscayaan.
Perspektif ecopolitics menunjukkan bahwa hilangnya pengawasan publik terhadap negara merupakan faktor risiko lingkungan yang sama berbahayanya dengan deforestasi. Ahli politik lingkungan seperti James C. Scott menyoroti bagaimana negara modern sering menciptakan legibility project, upaya menyederhanakan lanskap sosial-ekologis untuk kepentingan kontrol dan eksploitasi. Dalam proyek semacam itu, keberagaman sosial dan ekologis dipangkas agar investasi dapat bergerak “efisien”. Hutan menjadi “lahan”. Sungai menjadi “sumber daya air”. Masyarakat adat menjadi “pengguna kawasan”. Ketika kekayaan ekologis direduksi menjadi angka-angka, kritik pun ikut direduksi.
Fenomena Sumatra mencerminkan apa yang diperingatkan oleh ilmuwan hukum lingkungan Joseph Sax sejak 1970-an: the public trust doctrine hanya akan bermakna jika ada kekuatan sosial yang menjaga negara agar tidak mengkhianati amanah publik atas alam. Tanpa tekanan sipil, doktrin itu tinggal tulisan tanpa nyawa.
Hancurnya kontrol publik atas kebijakan lingkungan juga sejalan dengan temuan Political Ecology, sebuah pendekatan yang dikembangkan Michael Watts dan Piers Blaikie, bahwa degradasi lingkungan bukan semata persoalan ekologis, tetapi merupakan produk relasi kuasa yang timpang. Dalam kerangka ini, bencana seperti di Sumatra bukan sekadar “akibat perubahan iklim”, melainkan gejala dari extractive governance: model tata kelola yang dibentuk oleh logika ekstraksi, bukan perlindungan.
Dalam sistem extractive governance, watchdog publik dipreteli melalui tiga mekanisme yang kini terlihat jelas di Indonesia. Pertama, shrinking civic space: kriminalisasi aktivis, pengawasan jurnalis, dan tekanan terhadap LSM. Kedua, kooptasi melalui proyek, pendanaan, dan kemitraan semu yang membuat suara kritis meredup. Ketiga, produksi kebingungan sistemik: data yang tertutup, AMDAL yang manipulatif, dan narasi pembangunan yang membungkus eksploitasi dengan jargon hijau.
Ketika tiga mekanisme ini bekerja bersamaan, taring ekologis republik tercabut perlahan-lahan.
Padahal kekuatan penyeimbang itu sebenarnya ada. Ia hanya terserak, tercerai, dan tidak terkonsolidasi. Masyarakat adat yang mempertahankan hutan. Ilmuwan kampus yang terus menyimpan data. Jurnalis investigasi yang menelusuri izin-izin gelap. Komunitas perempuan yang menjaga mata air. Organisasi keagamaan yang menyuarakan etika lingkungan. Relawan kebencanaan yang tahu kondisi lapangan lebih baik daripada birokrasi mana pun. Mereka semua, jika disatukan, adalah check and balance ekologis yang bisa menahan laju kerusakan.
Di sinilah relevansi teori environmental citizenship dari Andrew Dobson. Dobson menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan tidak akan bertahan tanpa warga yang aktif menuntut akuntabilitas ekologis dari negara. Environmental citizenship bukan identitas moral, tetapi tindakan politik: keberanian untuk mengawasi, mempertanyakan, dan mempertahankan ruang hidup bersama.
Indonesia membutuhkan environmental citizenship itu sekarang, lebih dari kapan pun.
Kekuatan sipil harus kembali menjadi “taring ekologis”, bukan penonton pasif yang hanya menyaksikan bencana demi bencana. Pengawasan terhadap negara tidak bisa didelegasikan. Ia harus dihidupkan oleh pers independen, kampus yang merdeka, masyarakat adat yang diberi ruang, dan LSM yang tidak diteror. Tanpa itu, setiap NDC, setiap rencana adaptasi, setiap retorika “pembangunan hijau” hanya akan menjadi dokumen kosong yang tidak mampu menyelamatkan siapa pun.
Tragedi Sumatra seharusnya menjadi panggilan kebangkitan: bahwa republik tanpa taring ekologis adalah republik yang tak mampu menjaga masa depannya. Perubahan iklim memang menjadi pemicu, tetapi lumpuhnya pengawasan publik adalah alasan mengapa kerusakan itu tak terbendung. Jika kekuatan sipil tidak bangkit kembali, Indonesia akan terus menjadi negara yang kalah cepat dari iklim.
Dan iklim tidak pernah menunggu.
.png)
 44 minutes ago
1
44 minutes ago
1