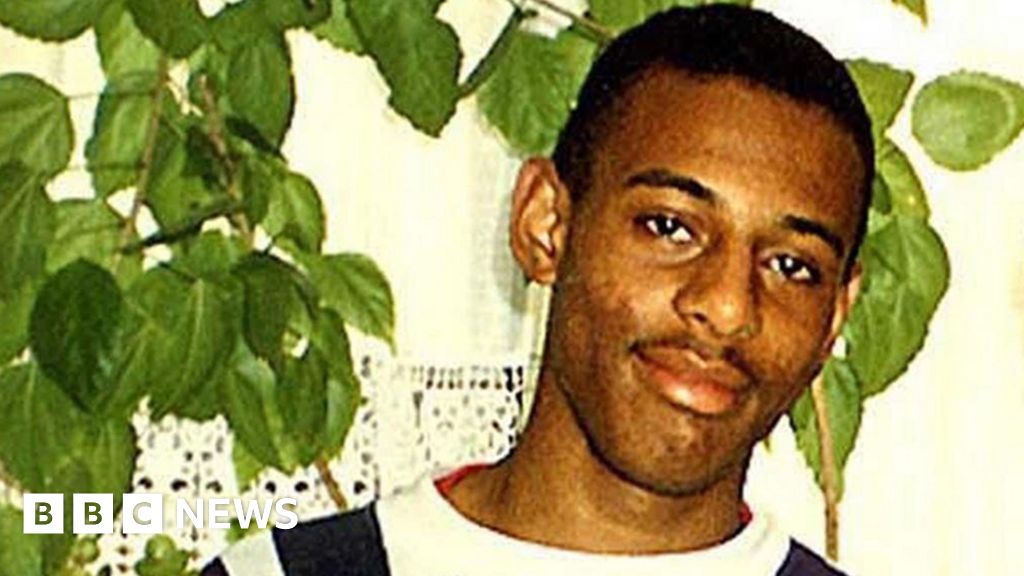Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Inkonsistensi Legislasi. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)
Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Inkonsistensi Legislasi. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA INDONESIA -- Konon, di negeri yang mengaku bernafaskan "negara hukum", setiap norma itu ibarat rambu lalu lintas. Dipaku kuat, dicat terang, tujuannya agar semua pengguna jalan negara tahu kapan mesti berhenti, kapan harus jalan, dan kapan wajib minggir agar tidak menabrak martabat konstitusi.
Di atas panggung aula Universitas Pamulang, Tengerang Selatan, Banten, Prof. Yusril Ihza Mahendra pagi itu mengingatkan kembali betapa rambu-rambu hukum kita sering diperlakukan seperti plang warung mie ayam: gampang dipindah, kadang dicopot, kadang disimpan di dapur, kadang dipasang miring, pokoknya terserah yang punya kuasa.
Yusril tidak sedang menguji mahasiswa. Ia menguji kesabaran bangsa. Sebab menurutnya, inkonsistensi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan lagi salah ketik atau salah tafsir, tetapi sudah mirip kasus salah alamat paket ekspedisi: MK bilang ke kiri, DPR bikin undang-undang belok ke kanan, pemerintah memutuskan lurus saja. Lalu semuanya sok bingung ketika negara tersesat di persimpangan.
Sejak amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga Mahkamah Konstitusi —yang kata Bu Megawati Soekarnoputri jumlah hakimnya sembilan karena meniru "Wali Songo"— MK diberi mandat sebagai Guardian of the Constitution. Penjaga kitab suci ketatanegaraan. Penafsir terakhir.
MK disepakati jadi hakim tertinggi yang bila sudah mengetukkan palu, bahkan bunyi kipas angin istana pun harus berhenti untuk memberi hormat. Putusannya final and binding: final, mengikat, dan tak bisa dilawan, kecuali Anda malaikat, atau politisi bandel yang merasa imunitasnya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar.
Masalahnya, kata Yusril, putusan yang final itu tidak selalu dilaksanakan secara final pula.
Ada undang-undang yang dibatalkan MK, tapi ketika DPR dan pemerintah menyusun revisi norma baru, isinya justru seperti pepatah orang hilang ingatan: "salah yang kemarin, besok diulang lagi."
Maka jadilah situasi ajaib di mana Mahkamah Konstitusi melepaskan tembakan roket, tapi pemerintah dan DPR menanggapinya dengan payung warna-warni. Tidak mati sih, tapi gosong sedikit.
Mari kita lihat contoh yang dibedah Yusril: Undang-Undang Cipta Kerja. MK menyatakan undang-undang itu inkonstitusional bersyarat. Pemerintah dan DPR diminta memperbaiki dalam waktu dua tahun.
Tapi alih-alih memperbaiki struktur undang-undang, negara malah mengeluarkan Perppu yang isinya —kata para pengamat— lebih mirip akrobat legislasi daripada refleksi atas putusan MK.
Belum selesai soal itu, muncul lagi perkara "pemilu serentak". MK dulu bilang pemilu presiden dan legislatif harus digabung. Pemerintah panik setengah mati, birokrasi ikut kejang ringan, partai politik mendadak sok bijak seolah mengerti makna "serentak" lebih dalam dari guru bahasa Indonesia. Semua direvisi tergesa-gesa.
Lalu apa yang terjadi? MK belakangan menggugat dirinya sendiri. Putusan baru menyatakan pemilu harus dibelah: pemilu pusat dan pemilu daerah dipisah. Sialnya, kedua putusan itu sama-sama _final and binding_.
Kalau dalam fikih ada istilah _nasikh-mansukh_, maka di MK versi modern inilah kita menyaksikan lahirnya mansukh tanpa nasikh dan nasikh tanpa mansukh dalam satu napas — semua berlaku, semua mengikat, dan semua bikin pusing pemerintah.
Yusril bertanya kepada Hamdan Zoelva, mantan Ketua MK, "Mana yang berlaku, putusan lama atau putusan baru?" Dan jawaban Hamdan sangat filosofis, nyaris sufistik: "Semua berlaku, Bang." Kalimat itu mungkin cocok ditulis di pintu gua pertapaan, tapi tidak untuk jadwal pemilu nasional.
Inkonsistensi legislasi ini, menurut Yusril, muncul karena tiga sumber: politik, tafsir, dan ego kekuasaan.
Pertama, politik. Jangan membayangkan pembentukan undang-undang itu pekerjaan sakral seperti menyalin mushaf. Ia lebih mirip rapat panitia konsumsi hajatan desa.
Semua pihak datang membawa kepentingannya masing-masing, dan setiap norma adalah hasil tarik-menarik antara ideologi, lobi, dan janji-janji yang hanya Tuhan dan notulen rapat yang tahu kebenarannya.
Kedua, tafsir. Yusril mengingatkan: teks undang-undang tidak pernah turun dari langit seperti hujan meteor. Ia ditafsirkan ulang oleh generasi yang hidup pada konteks berbeda. Apa yang menurut pembentuk undang-undang bermakna A, bisa berubah menjadi AB versi MK, dan menjadi AC setelah dibaca di DPR.
Semuanya merasa paling benar, padahal yang benar hanya satu: konstitusi. Tapi siapa penafsir final? MK. Siapa pembuat norma? DPR dan Presiden. Siapa yang paling keras kepala? Tentu saja semuanya.
Ketiga, ego kekuasaan. Yusril menggambarkan situasinya dengan humor sinis tapi tepat sasaran. "Undang-undang dibuat oleh Presiden dan DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Dibatalkan oleh sembilan hakim MK. Sembilan orang ini siapa? Malaikatkah?"
Pertanyaan itu bukan cemoohan, tetapi peringatan: jangan jadikan konstitusi sebagai gelang karet yang bisa ditarik ke segala arah.
Lalu bagaimana akibat inkonsistensi ini? Pertama, kepastian hukum runtuh pelan-pelan. Kalau setiap putusan dapat dipatuhi, tetapi boleh juga diakali lewat revisi yang berlawanan, maka norma bukan lagi pagar, tetapi kain korden yang bisa digeser ke kanan-kiri.
Kedua, legitimasi MK dipertanyakan. Bagaimana mungkin dua putusan berbeda keduanya final? Bagaimana jika MK kelak bersengketa dengan Presiden dan DPR terkait kewenangan legislasi, dan perkara itu harus diadili MK sendiri? Negara bisa macet total, bukan karena kudeta, tetapi karena logika hukum mogok.
Ketiga, kepercayaan publik luruh, seperti cat tembok terpapar hujan deras. Rakyat semakin sulit memahami mana hukum yang harus dipatuhi, mana aturan yang sekadar basa-basi politik.
Namun, sebagaimana biasa, Yusril tidak menutup pidatonya dengan keputusasaan. Ia memberi resep: perlunya _legislative review_ pasca putusan MK, dan perlunya etika konstitusional di DPR maupun pemerintah.
DPR tidak boleh membuat undang-undang hanya untuk "mengakali putusan MK", seperti menambal ban bocor dengan stiker lucu. Dan terutama, negara harus kembali menghormati konstitusi sebagai norma tertinggi, bukan bros manis di dada setiap pejabat.
Walhasil, inkonsistensi legislasi pasca putusan MK bukan sekadar masalah teknis hukum. Ia cermin kualitas jiwa kita sebagai bangsa. Bangsa yang sebenarnya tahu arah, tetapi sering pura-pura tersesat demi kepentingan sesaat. Bangsa yang tahu jalan pulang ke rumah konstitusi, tapi memilih berputar-putar di bundaran kekuasaan.
Padahal, seperti kata Yusril, negara hukum bukan tentang siapa yang lebih keras berteriak, tetapi siapa yang paling patuh pada aturan yang dibuatnya sendiri.
Bila rambu-rambu hukum dipasang untuk ditabrak, maka jangan salahkan kalau negara suatu hari hanya jadi museum peradaban: banyak aturan, sedikit kepastian; banyak pasal, sedikit keadilan.
Barangkali di situlah ironi kita: negara hukum yang sibuk menulis hukum, tetapi malas menjalankannya. (***)
Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 9/12/2025
.png)
 1 hour ago
1
1 hour ago
1